STUDI
ETNOBOTANI KERAJIANAN ANYAMAN ROTAN OLEH MASYARAKAT KELURAHAN BALEARJOSARI
MALANG
JAWA
TIMUR
MAKALAH
Disusun
untuk memenuhi tugas akhir semester matakuliah
Etnobotani
yang
dibina oleh Bapak Dr. Eko Budi Minarno, M.Pd.
Oleh:
Juliana Afni sitorus
12620063
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS
SAINTEK
JURUSAN
BIOLOGI
Juni 2015
KATA PENGANTAR
Puji
syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat,
taufik, serta hidayah-Nya sehingga makalah ini dapat terselesaikan tepat pada
waktunya. Makalah ini mengkaji tentang Studi Etnobotani Kerajianan Anyaman
Rotan Oleh Masyarakat Kelurahan Belearjosari Malang Jawa Timur. Makalah ini
disusun guna untuk memenuhi tugas Etnobotani. Penyusun berharap semoga makalah
ini dapat memberi manfaat bagi pembaca untuk menambah.
Tidak
lupa penyusun menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berperan
aktif dalam penyusunan makalah
ini. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik, lancar, dan
tepat waktu. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.
Dr.
H. Eko Budi Minarno, M.Pd sebagai dosen pengampu mata kuliah Etnobotani yang memberikan
dukungan bagi penulis
2.
Bapak Iwan, Bapak Mul dan Cindy Rotan yag telah berkenan memberi informasi dan bimbingannya
kepada penulis
3.
Orang
tua yang selalu mendo’akan demi kelancaran penulis
4.
Teman-teman
yang selalu mendukung dan memberi semangat bagi penulis
Kesempurnaan
hanya milik Allah, sedangkan kekurangan pada hamba-Nya, begitu pula dengan makalah ini tidak akan sempurna
tanpa kritik dan saran dari pembaca. Oleh karena itu, kritik dan saran dari
pembaca sangat penyusun butuhkan untuk melengkapi makalah ini.
Malang,
11 Juni 2015
Penulis
DAFTAR ISI
3.1 Jenis Penelitian
3.3 Alat dan Bahan
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia merupakan negara yang memiliki budaya yang
sangat beraneka ragam, ini merupakan daya tarik tersendiri yang dimiliki
Indonesia. Kebudayaan yang timbul merupakan kebudayaan yang diturunkan secara
turun temurun, yang dapat dikatakan sebagai kearifan lokal, kebudayaan yang
terdapat di Indonesia memiliki karakter yang berbeda sesuai adat dan aturan
yang berlaku di masyarakat. Salah satu tradisi budaya yang telah berkembang secara
turun temurun yaitu adalah kerajinan anyaman. Anyaman merupakan suatu produk
yang dihasilkan dari kegiatan mengatur bilah-bilah seperti pandan, bambu, dan
bahan lainnya tindih menindih atau silang menyilang.
Menurut beberapa sumber keterampilan anyaman masuk
ke Indonesia sejak beberapa ribu tahun lalu, ketika migrasi besar-besaran
penduduk dari dataran Asia Tengah menuju ke Nusantara, keterampilan itu terus
berlanjut hingga sekarang. Di beberapa tempat di Indonesia anyaman berkembang
menjadi suatu komoditas yang menjanjikan, namun beberapa sumber mengatakan
bahwa anyaman merupakan kebudayaan asli bangsa melayu, termasuk Indonesia,
tanpa adanya pengaruh dari dunia luar.
Rotan adalah palem
pemanjat berduri yang terdapat didaerah tropis dan subtropis. Tumbuhan ini
merupakan sumber rotan batang untuk industri mebel rotan. Rotan mempunyai
sifat-sifat yang alami yaitu elastis, mudah dibentuk, ringan, tahan terhadap
perubahan cuaca, dan mempunyai warna alamiah yang menarik. Dengan
sifat-sifatnya tersebut rotan dapat digunakan sebagai bahan dalam pembuatan
berbagai peralatan rumah tangga seperti berbagai jenis mebel, tikar, peralatan
dapur dan berbagai jenis barang kerajinan lainnya. Karakteristik itu juga
mengakibatkan banyak konsumen yang menyukai barang-barang kerajinan hasil dari
rotan. Pemanfaatan rotan untuk kerajinan, sebagian besar berasal dari batang.
Ahli rotan, Janumirno (2000) mengatakan bahwa
pada abad ke-18 Indonesia telah menjadi pelopor dalam penyediaan produk rotan
dunia, yakni hampir 80% keperluan dunia dipasok dari Indonesia. Indonesia mulai
mengenal industri pengolahan rotan pada tahun 1968-1973, dan berkembang pesat
sekitar tahun 1988.
Menurut
Baharuddin dan Taskirawati, (2009), Indonesia merupakan negara produsen rotan
yang mampu memenuhi kebutuhan rotan dunia, dan selama ini mampu memasok kurang
lebih 85% dari kebutuhan rotan di dunia. Di Indonesia terdapat kurang lebih 306
spesies rotan telah teridentifikasi dan menyebar di semua pulau di Indonesia.
Dari keseluruhan yang teridentifikasi, rotan yang sudah ditemukan dan digunakan
untuk keperluan lokal mencapai kurang lebih 128 jenis. Sementara itu rotan yang
sudah umum diusahakan/ diperdagangkan dengan harga tinggi untuk berbagai
keperluan baru mencapai 28 jenis saja.
Kelurahan
Balearjosari adalah salah satu daerah kota Malang yang terkenal dengan produksi
dan penjualan kerajinan anyaman berbahan rotan.
Berbagai kerjinan dihasilkan dari bahan dasar rotan. Rotan yang
digunakan adalah rotan besar dan rotan kecil. Adakala bahan kerajinan rotan dikombinasikan
dengan bahan lain seperti serat eceng gondok, serat pelepah pisang dan
lain-lain. Pemanfatan tumbuhan dengan sebaik-baiknya telah termaktub dalam
al-Qur’an surah Az-Zumar (21):
 |
Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diatur-Nya menjadi sumber-sumber air di bumi Kemudian
ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu
menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, Kemudian dijadikan-Nya
hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal.
Dari ayat di atas dapat
diketahui bahwa Allah SWT memerintahkan manusia memikirkan salah satu dari
suatu proses kejadian di alam ini yaitu proses turunnya hujan dan tumbuhnya
tumbuh-tumbuhan di permukaan bumi. Apabila diperhatikan seakan-akan kejadian
hujan merupakan suatu siklus yang dimulai pada suatu titik-titik dalam suatu
lingkaran, dimulai dari adanya sesuatu, kemudian berkembang menjadi besar,
kemudian tua, kemudian meninggal atau tiada. Kemudian mulai pula suatu kejadian
yang baru lagi dan begitulah seterusnya sampai kepada suatu masa yang
ditentukan Allah, yaitu masa berakhirnya kejadian alam
Adakalanya air hujan tersebut
langsung dimanfaatkan oleh manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Dengan air
hujan maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, sejak dari benih kemudian menjadi besar,
berbunga yang beraneka warna, berbuah, kemudian mati, untuk tumbuh lagi.
Buahnya bermanfaat bagi manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Ada yang
dimakan, ada pula yang diolah untuk keperluan-keperluan lain. Daun
tumbuh-tumbuhan yang gugur kemudian menjadi hancur bersama tanah dapat menjadi
pupuk bagi bagi tanam-tanaman yang lain. Maha suci Allah yang telah menciptakan
tumbuh-tumbuhan dengan berbagai manfaat demi kebutuhan manusia. Sungguh yang
demikian terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal.
Pemanfaatan tumbuhan seperti rotan
untuk bahan kerajian anyaman sudah menjadi tradisi turun-temurun dari generasi
ke generasi. Satu jenis bahan anyaman yang sering digunakan adalah rotan.
Selain mudah diperoleh dan populasinya melimpah rotan mempunyai nilai fungsi
yang sangat diminati masyarakat umun sehingga anyaman rotan menjadi sumber
ekonomi yang menjanjikan. Oleh karena itu perlu dilakukan observasi dengan
judul Studi Etnobotani
Kerajianan Anyaman Rotan Oleh Masyarakat Kelurahan Belearjosari Malang Jawa
Timur.
1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian
ini dipaparkan sebagai berikut.
1. Jenis
tumbuhan apa saja yang dapat dimanfaatkan dalam kerajianan anyaman oleh
masyarakat kelurahan Balearjosari?
2. Organ apasajakah yang dimanfaatkan dalam kerajinan anyaman rotan?
3. Darimana sajakah bahan diperoleh untuk kerjajinan anyaman rotan
?
4. Bagaimana
teknik pembuatan kerajinan anyaman?
5. Bagaimana
kelemahan dan kelebihan rotan sebagai bahan kerajinan anyaman?
1.3 Tujuan
Tujuan
dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut.
1. Jenis
tumbuhan yang dapat dimanfaatkan dalam kerajianan anyaman oleh masyarakat
kelurahan Balearjosari
2. organ yang dimanfaatkan dalam kerajinan anyaman rotan
3. tempat perolehan bahan untuk kerjajinan anyaman rotan
4. teknik
pembuatan kerajinan anyaman
5. kelemahan
dan kelebihan rotan sebagai bahan kerajinan anyaman
1.4 Manfaat
Manfaat dari penelitian ini adalah
sebagai berikut.
1. Sebagai
informasi kepada masyarakat luas dan penulis tentang potensi rotan dalam
kerajinan anyaman
2. Sebagai informasi
kepada masyarakat luas dan penulis teknik pembuatan kerajinan anyaman dari
rotan
3. Sebagai dokumentasi etnobotani tumbuhan untuk bahan kerajinan
anyaman yang patut dilestarikan sebagai warisan budaya
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 Etnobotani
2.1.1 Pengertian Etnobotani
Etnobotani
menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah ilmu botani mengenai pemanfaatan
tumbuh-tumbuhan dalam keperluan kehidupan sehari-hari dan adat suku bangsa.
Etnobotani berasal dari dua kata yunani yaitu Ethnos dan botany.
Etno berasal dari kata ethnos yang berarti memberi ciri pada kelompok dari
suatu populasi dengan latar belakang yang sama baik dari adat istiadat,
karekteristik, bahasa dan sejarahnya, sedangkan botani adalah ilmu yang
mempelajari tentang tumbuhan. Dengan demikian etnobotani berarti kajian
interaksi antara manusia dengan tumbuhan atau dapat diartikan sebagai studi
mengenai pemanfaatan tumbuhan pada suatu budaya tertentu (Martin 1998).
Beberapa
definisi etnobotani yang lain menurut beberapa penulis yang diacu dalam Soekarman dan Riswan (1992),
antara lain:
1. Hough
(1898), etnobotani adalah ilmu yang mempelajari tumbuh-tumbuhan dalam
hubungannya dengan budaya manusia,
2. Jones
(1941), etnobotani adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia yang
primitif dengan tumbuh-tumbuhan,
3. Schultes
(1967), etnobotani adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan
vegetasi di sekitarnya,
4. Ford
(1980), etnobotani adalah ilmu yang mempelajari penempatan tumbuhan secara
keseluruhan didalam budaya dan interaksi langsung manusia dengan tumbuhan,
5. Sheng-Ji
et al. (1990), etnobotani adalah ilmu yang mempelajari keseluruhan
hubungan langsung antara manusia dan tumbuhan untuk apa saja kegunaannya.
Dari beberapa
pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa etnobotani merupakan ilmu yang
mempelajari hubungan langsung manusia dengan tumbuhan dalam kegiatan
pemanfaatannya secara tradisional (Soekarman
& Riswan 1992). Seiring dengan perkembangan imu pengetahuan serta
teknologi, maka etnobotani berkembang menjadi suatu bidang imu yang cakupanya
interdisipliner. Etnobotani secara harfiah berarti ilmu berarti ilmu yang
menkaji pengetahuan botani masyarakat lokal atau tradisional. Etnobotani dapat
diidentifikasikan sebagai suatu bidang yang mempelajari hubungan timbal balik
secara menyeluruh antara masyarakat lokal dengan lingkungannya meliputi sistem
pengetahuan tentang sumberdaya alam tumbuhan (Ferdiansyah, 2009).
2.1.2 Ruang Lingkup
Etnobotani
adalah cabang ilmu pengetahuan yang mendalami tentang persepsi dan konsepsi
masyarakat tentang sumber daya nabati di lingkungannya. Dalam hal ini adalah
upaya untuk mempelajari kelompok masyarakat dalam mengatur sistem pengetahuan
anggotanya menghadapi tetumbuhan dalam lingkungannya, yang digunakan tidak saja
untuk keperluan ekonomi tetapi juga untuk keperluan spiritual dan nilai budaya
lainnya. Dengan demikian termasuk kedalamnya adalah pemanfaatan tumbuhan oleh
penduduk setempat atau suku bangsa tertentu. Pemanfaatan yang dimaksud disini
adalah pemanfaatan baik sebagai bahan obat, sumber pangan, dan sumber kebutuhan
hidup manusia lainnya. Sedangkan disiplin ilmu lainnya yang terkait dalam
penelitian etnobotani adalah antara lain linguistik, anthropologi, sejarah, pertanian,
kedokteran, farmasi dan lingkungan (Suwahyono 1992).
Terdapat empat usaha
utama yang berkaitan erat dengan etnobotani, yaitu: 1) pendokumentasian
pengetahuan etnobotani tradisional; 2) penilaian kuantitatif tentang
pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber botani; 3) pendugaan tentang
keuntungan yang dapat diperoleh dari tumbuhan, untuk keperluan sendiri maupun
untuk tujuan komersial; dan 4) proyek yang bermanfaat untuk memaksimumkan nilai
yang dapat diperoleh masyarakat lokal dari pengetahuan ekologi dan
sumber-sumber ekologi (Martin 1998).
2.2. Kerajinan Anyaman
2.2.1 Pengertian Kerajinan Anyaman
Kerajinan anyaman merupakan satu
usaha atau kegiatan keterampilan masyarakat dalam pembuatan barang-barang
dengan cara atau teknik susup menyusup antara lungsing dan pakan. Menganyam
pada dasarnya menyelipkan secara pelan-pelan, diantaranya lusi-lusi. Lusi
adalah bilah-bilah yang posisinya membujur ke atas dan pakan yang melintang ke
samping. Dengan memperhatikan corak anyaman baik, langsung maupun melalui
gambar, siapa pun bisa mencoba menganyam, asal mengikuti ketentuan atau rumus
pada setiap motif anyaman.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
dalam Seminar Nasional Seni Kriya (2005:153) istilah kerajinan berasal dari
bahasa jawa yang berarti; (1) hal atau sifat dan sebagainya; (2) kegotalan,
industri, perusahaan yang membuat sesuatu,atau pekerjaan tangan yang bukan
dengan mesin melainkan menggunakan tangan. Kerajinan tersebut di produksi
mengutamakan bahan-bahan yang layak terdapat di daeah sekitarnya dan alat yang
digunakan sangat sederhana.dikerjakan sangat terampil dan penuh hati-hati,
(Suptandar, dalam Wahyuningsih, Seminar Nasional Seni Kriya; 2005:153). Dari
beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kerajinan adalah hasil
pekerjaan tangan yang bukan dilakukan dengan mesin melainkan menggunakan tangan
yang dibuat dengan penuh hati-hati dan menggunakan bahan dan alat yang
sederhana.
Anyaman merupakan seni yang
mempengaruhi kehidupan dan kebudayaan masyarakat Melayu. Konon kegiatan itu
ditiru manusia dari cara burung menjalin rantin ranting menjadi bentuk yang
kuat. Menganyam adalah proses menjaringkan atau menyilangkan bahan
tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan satu rumpun yang kuat dan dapat digunakan.
Contoh tumbuh-tumbuhan yang dianyam
seperti lidi, rotan, akar-akaran, serat
eceng gondok, serat pelepah pisang, daun pandan, dan beberapa bahan tumbuhan
lain yang dikeringkan. Menganyam adalah salah satu seni tradisi tertua di
dunia. Kesenian ini juga ada di berbagai budaya Nusantara. Di rumah-rumah
panggung di pesisir Aceh,tikar pandan menjadi alas lantai. Di Pedamaran,
Sumatra Selatan, kegiatan menganyam tikar menjadi pemandangan sehari-hari yang
dilakukan ibu dan para gadis remaja.
2.2.2 Sejarah Anyaman
Seni anyaman adalah milik
masyarakat melayu yang masih sangat di kagumi dan di gemari hingga saat ini.
Kegiatan seni anyaman telah ada sejak dahulu kala. Hal ini dapat dilihat pada dinding
rumah orang jaman dahulu dianyam dengan menggunakan buluh. Seni anyaman dipercaya
bermula dan berkembangnya tanpa menerima pengaruh luar. Penggunaan tali, akar,
dan rotan merupakan asas pertama dalam penciptaan kerajinan tangan anyaman.
Bahan-bahan anyaman tumbuh liar di hutan-hutan, kampung-kampung, dan kawasan
sekitar pantai. Berbagai bentuk kerajinan tangan dapat di bentuk melalui proses
dan teknik anyaman dari jenis tumbuhan pandan dan bengkuang.
Bentuk-bentuk anyaman dibuat
berdasarkan fungsinya. Masyarakat petani atau nelayan anyaman dibentuk menjadi topi,
bakul, tudung saji, tikar, dan lain-lain untuk digunakan dalam keseharian. Selain
dari tumbuhan pandan, anyaman juga dapat di buat dari tumbuhan jenis palma dan
nipah. Seni anyaman merupakan daya cipta dari sekelompok masyarakat luar istana
yang lebih mengutamakan nilai kegunaannya. Walaupun pada tahun 1756 sampai 1794
telah terdapat penggunaan tikar untuk raja yang terbuat dari rotan.
2.2.3 Jenis-Jenis Kerajinan Anyaman
Setiap produk mungkin saja memiliki jenis anyaman
yang sama atau berbeda. Jenis anyaman memang bermacam-macam. Setiap jenis
berbeda cara mengerjakannya. Anyaman yang sering digunakan adalah anyaman
sasag, anyaman kepang, dan anyaman bersegi. Anyaman sasag banyak digunakan
untuk pembuatan keranjang, anyaman kepang untuk pembuatan bilik, anyaman
bersegi untuk pembuatan kursi rotan.

Gambar 1. Jenis Anyaman Sasag

 Gambar
2. Jenis Anyaman Kepang
Gambar
2. Jenis Anyaman Kepang
Gambar
3. Jenis anyaman bersegi
2.3 Tanaman Rotan
2.3.1 Anatomi Tanaman Rotan
Struktur anatomi batang rotan dikelompokkan menjadi
2 (dua), yaitu: ciri umum dan ciri anatomi. Ciri umum meliputi warna batang,
diameter batang, panjang ruas dan tinggi
buku, sedangkan ciri anatomi meliputi dimensi ikatan pembuluh, berkas serat,
serat, pembuluh metaksilim, protoksilem dan floem. Ciri anatomi rotan digunakan
sebagai kunci identifikasi jenis, karena ciri umum banyak memiliki persamaan
karena penilaiannya dilakukan dengan panca indera yang sifatnya tidak konstan
dan subyektif. Ciri anatomi juga digunakan untuk menentukan sifat-sifat
kekuatan, mutu dan cara pengolahannya (Rachman dan Jasni, 2006 dan Jasni dkk,
2012). Secara garis besar rotan terdiri dari 3 (tiga) jaringan utama.
1.
Kulit
Kulit terdiri dari 2 (dua) lapis sel yaitu epidermis
dan endodermis. Sel epidermis dapat berbentuk empat persegi panjang, bujur
sangkar dan pipa kadang-kadang terdapat silika. Sel endodermis berbentuk
barisan serat atau pita serat yang bersifat lebih lunak. Sel ini diduga sebagai
tempat pembentukan persenyawaan silika yang selanjutnya diendapkan pada
epidermis.
2. Parenkim dasar
Jaringan parenkim dasar merupakan pengisi batang
rotan dengan ikatan-ikatan pembuluh tertanam dan menyebar didalamnya. Parenkim
dasar terdiri dari sel-sel parenkim isodiometrik berdinding tipis dengan noktah
sederhana.
3. Ikatan pembuluh
Jaringan ikatan pembuluh terletak menyebar diantara
jaringan parenkim dasar. Pada penampang lintang rotan ikatan pembuluh dapat
dilihat berupa bintik-bintik. Jaringan ikatan pembuluh terdiri dari beberapa
macam sel, yaitu: metaksilim, protoksilim, phloem, parenkim aksial. Jaringan
pembuluh sebagai jaringan pelaksana yang mengatur kegiatan fisiologis tanaman
dan serat sebagai jaringan penyangga yang memberi kekuatan mekanik. Phloem
adalah jaringan yang berfungsi sebagai penyalur dan pembawa hasil fotosintesis
dari tajuk kebagian lain dari tanaman. Bentuknya seperti pipa yang sambung
menyambung dengan bidang perforasi berbentuk tapisan. Sedangkan metaksilim dan
protoksilim merupakan jaringan yang berfungsi sebagai saluran air dan zat hara
dari akar ke daun.
Parenkim aksial menyebar disekeliling metaxilem,
ptoroksilim dan phloem di dalam ikatan pembuluh. Saluran getah tersebar
diantara jaringan parenkhim dasar yang dapat ditemui pada beberapa jenis rotan
seperti pada Daemonorops, Ceratalobus dan beberapa jenis Calamus.
Saluran ini mengeluarkan zat ekstraktif. Stegmata adalah sel yang berisi
partikel silika. Stegmata semakin banyak terdapat kearah jaringan kulit.
Selanjutnya partikel silika ini yang menentukan kekerasan batang rotan.
Penyusun utama rotan adalah sel parenkhim, sel serat dan pori. Komposisi
sel-sel ini sangat berperan dalam menentukan sifat fisika dan mekanika rotan
(Rachman, 1996).
2.3.2 Morfologi Tumbuhan Rotan
Rotan
merupakan palem berduri yang memanjat dan hasil hutan bukan kayu yang
terpenting di Indonesia (MacKinnon et al., 2000). Rotan dapat berbatang
tunggal (soliter) atau berumpun. Rotan yang tumbuh soliter hanya dipanen sekali
dan tidak berregenerasi dari tunggul yang terpotong, sedangkan rotan yang
tumbuh berumpun dapat dipanen terus-menerus. Rumpun terbentuk oleh
berkembangnya tunas-tunas yang dihasilkan dari kuncup ketiak pada bagian bawah
batang. Kuncup-kuncup tersebut berkembang sebagai rimpang pendek yang kemudian tumbuh menjadi batang di atas permukaan
tanah (Dransfield dan Manokaran, 1996).
Akar tanaman rotan
mempunyai sistem perakaran serabut, berwarna keputih-putihan atau
kekuning-kuningan serta kehitam-hitaman. Batang tanaman rotan berbentuk
memanjang dan bulat seperti silinder tetapi ada juga yang berbentuk segitiga.
Batang tanaman rotan terbagi menjadi ruas-ruas yang setiap ruas dibatasi oleh
buku-buku. Pelepah dan tangkai daun melekat pada buku-buku tersebut. Tanaman
rotan berdaun majemuk dan pelepah daun yang duduk pada buku dan menutupi
permukaan ruas batang. Daun rotan ditumbuhi duri, umumnya tumbuh mengahadap ke
dalam sebagai penguat mengaitkan batang pada tumbuhan inang. Rotan termasuk
tumbuhan berbunga majemuk. Bunga rotan terbungkus seludang. Bunga jantan dan
bunga betina biasanya berumah satu tetapi ada pula yang berumah dua. Karena
itu, proses penyerbukan bunga dapat terjadi dengan bantuan angin atau serangga
penyerbuk. Buah rotan terdiri atas kulit luar berupa sisik yang berbentuk
trapezium dan tersusun secara vertikal dari toksis buah. Bentuk permukaan buah
rotan halus atau kasar berbulu, sedangkan buah rotan umumnya bulat, lonjong
atau bulat telur (Januminro, 2000).
Tempat
tumbuh rotan pada umumnya di daerah tanah berawa, tanah kering, hingga tanah
pegunungan. Tingkat ketinggian tempat untuk tanaman rotan dapat mencapai 2900
meter di atas permukaan laut (mdpl). Semakin tinggi tempat tumbuh semakin
jarang dijumpai jenis rotan. Rotan juga semakin sedikit di daerah yang berbatu
kapur. Tanaman rotan menghendaki daerah yang bercurah hujan antara
2000mm-4000mm per tahun menurut tipe iklim Schmidt dan Ferguson, atau daerah
yang beriklim basah dengan suhu udara berkisar 24 oC-30 oC. Tanaman rotan yang
tumbuh dan merambat pada suatu pohon akan memiliki tingkat pertumbuhan batang
lebih panjang dan jumlah batang dalam satu rumpun lebih banyak jika
dibandingkan dengan rotan yang menerima sedikit cahaya matahari akibat tertutup
oleh cabang, ranting dan daun pohon (Januminro, 2000).
2.3 Manfaat Rotan
Batang
rotan yang sudah tua banyak dimanfaatkan untuk bahan baku kerajinan dan perabot
rumah tangga. Batang yang muda digunakan untuk sayuran, akar dan buahnya untuk
bahan obat tradisional. Getah rotan dapat digunakan untuk bahan baku pewarnaan
pada industri keramik dan farmasi. Manfaat tidak langsung dari rotan adalah
kontribusinya meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan, peranannya
dalam membentuk budaya, ekonomi, dan sosial masyarakat. Batang rotan dapat
dibuat bermacam-macam bentuk perabot rumah tangga atau hiasan-hiasan lainnya.
Misalnya mebel, kursi, rak, penyekat ruangan, keranjang, tempat tidur, lemari,
lampit, sofa, baki, pot bunga, dan sebagainya (Januminro, 2000).
Rotan
mempunyai keterkaitan yang rumit dengan binatang-binatang di dalam hutan
seperti tumbuh-tumbuhan lainnya dalam hutan basah tropis. Banyak rotan yang
memberi tempat kehidupan bagi semut dalam helaian daun, duri, dan batangnya
mungkin hal ini merupakan suatu perlindungan terhadap pemangsaan. Dalam
hubungan timbal balik antara semut dan rotan, semut memelihara kutu-kutu
bertepung yang menghasilkan embun madu. Bunga rotan berbau harum dan
penyerbukan bergantung pada serangga termasuk semut, kumbang, trips, lebah, dan
lalat. Burung, kera, monyet dan luang diperkirakan merupakan pemencar biji
rotan yang penting (MacKinnon et al., 2000).
2.4 Pengolahan Rotan
Jasni et al. (2000) mendefinisikan pengolahan
rotan sebagai suatu kegiatan pengerjaan lanjutan terhadap bahan baku rotan
bulat (rotan asalan) menjadi barang setengah jadi dan barang jadi serta siap
dipakai dan dijual. Tahapan pengolahan rotan dibedakan atas penanganan rotan pasca
panen di hutan dan di industri. Rachman dan Hermawan (2005) mengklasifikasikan
rotan kecil adalah rotan dengan diameter <16 mm dan rotan besar adalah rotan
dengan diameter >16 mm. Contoh rotan kecil adalah rotan sega, irit,
jermasin, pulut, dan lain-lain, sedangkan contoh rotan besar adalah rotan
manau, tohiti, semambu, batang, dan lain-lain.
2.4.1. Penanganan Rotan Pasca Panen di Hutan
Menurut Rachman et al. (2000), rotan
dikatakan masak tebang apabila lebih dari tiga perempat pelepah yang menempel
pada batang telah mengelupas dan meluruh ke tanah dan sebagian duri berwarna
kehitaman serta telah rontok. Rotan besar umumnya masak tebang pada kisaran
umur 15-20 tahun dengan panjang batang berkisar antara 30-60 m, sedangkan rotan
kecil dapat ditebang pada umur tujuh tahun dengan kisaran panjang batang antara
20-30 m (Rachman et al., 2000). Setelah ditebas dan ditarik, rotan segera
dibersihkan dari pelepah dan duri dengan menggunakan parang atau golok secara
hati-hati agar tidak merusak kulit rotan.
Rachman et al. (2000) menjelaskan perlakuan
yang diberikan kepada rotan berukuran diameter besar sebagai berikut: setelah
dibersihkan, rotan yang berdiameter besar kemudian dipotong-potong sesuai
ukuran panjang (sekitar 2,5 m atau lebih) dan dipisahkan dari bagian pangkal
rotan yang terlalu keras maupun bagian ujung yang masih muda. Potongan-potongan
rotan ini kemudian diluruskan dengan cara menjepitkannya pada 2 batang pohon
yang berdekatan atau cagak pohon sambil ditekan hati-hati agar rotan tidak patah.
Potongan-potongan rotan tersebut kemudian diikat dengan tali bambu/rotan kecil
menjadi bundelan-bundelan yang masing-masing berisi 25 potong - 60 potong.
Bundelan-bundelan ini kemudian diangkut ke tepi hutan dan diletakkan di tempat
yang teduh di lokasi penampungan sementara dengan diberi ganjal di bagian
bawahnya agar tidak langsung berhubungan dengan tanah. Apabila rotan tidak
langsung dibawa ke industri/tempat penggorengan dalam jangka waktu 5 hari
setelah diangkut dari hutan, disarankan agar rotan sebaiknya diawetkan terlebih
dahulu untuk mencegah serangan jamur biru, penggerek basah, dan kumbang
ambrosia. Secara sederhana, pengawetan dapat dilakukan dengan merendam rotan
dalam larutan bahan pengawet selama 2-4 jam.
Untuk rotan yang berukuran diameter kecil, setelah
dipanen dan dibersihkan dari daun dan duri, rotan yang memiliki lapisan silika
dibersihkan dahulu dengan menggunakan alat runti. Setelah itu, rotan dapat
dipotong-potong dengan panjang sesuai permintaan dan dipisahkan dari bagian
pangkal yang keras maupun bagian ujung yang lunak. Selanjutnya, rotan dicuci
dalam air mengalir dan digosok dengan karung goni yang diberi pasir atau sabut
kelapa sampai rotan bersih dari kotoran. Rotan kemudian disusun ke arah
memanjang sebanyak 35-70 potong dan kemudian ditekuk menjadi setengahnya serta
diikat dengan tali bambu atau belahan rotan. Apabila rotan terlambat diangkut
ke industri pengolahan, sebaiknya rotan juga diawetkan dengan prosedur yang
sama dengan rotan besar (Rachman et al., 2000).
2.4.2 Pengolahan Rotan di Industri
Sebagaimana halnya dengan penanganan rotan pasca
panen di hutan, terdapat sedikit perbedaan dalam pengolahan awal untuk rotan
dengan ukuran diameter besar dengan rotan berdiameter kecil. Dibandingkan
dengan rotan besar, proses pengolahan awal rotan kecil lebih sederhana. Pada
umumnya, rotan kecil tidak perlu digoreng sebagaimana halnya rotan besar karena
dapat mengering lebih cepat. Beberapa langkah yang dilakukan dalam proses
pengolahan awal rotan adalah sebagai berikut (Rachman et al., 2000) :
1.
Persiapan
Tahapan persiapan terdiri atas kegiatan penumpukan
rotan segar, pembersihan, dan sortasi. Rotan yang diterima di tempat penumpukan
adalah rotan yang berkualitas baik dan sudah cukup tua dengan ciri-ciri
diameter silindris, cukup keras, tidak ada tanda-tanda keriput, dan mengandung
lebih banyak warna hijau tua .
2.
Penggorengan
Tujuan penggorengan rotan adalah untuk menurunkan
kadar air rotan dan mengeluarkan bahan-bahan larut minyak yang umumnya terdapat
di bagian kulit (epidermis) rotan serta dapat menghalangi proses keluarnya air
dari dalam rotan. Dengan melakukan penggorengan, waktu penjemuran rotan di lapangan
dapat lebih singkat, sekitar 1-2 minggu sehingga dapat mengurangi kemungkinan
serangan jamur atau serangga perusak rotan. Selain itu, warna rotan yang
digoreng menjadi lebih cerah.
3.
Penggosokan dan pencucian
Penggosokan dilakukan pada rotan yang telah digoreng
dan ditiriskan dengan menggunakan kain perca, sabut kelapa atau karung goni
yang dicampurkan dengan pasir halus atau serbuk gergaji (Jasni et al., 2000).
Penggosokan dilakukan berulang-ulang agar sisa kotoran terutama getah yang
masih menempel pada kulit rotan dapat dilepaskan sehingga kulit rotan menjadi
bersih dan dapat diperoleh rotan dengan warna yang cerah dan mengkilap.
Bersama-sama dengan penggosokan, rotan juga dapat dicuci untuk membersihkan
rotan secara sempurna.
4.
Peruntian
Peruntian dilakukan untuk membuang lapisan silika
yang melekat pada kulit beberapa jenis rotan kecil. Beberapa jenis rotan yang
umumnya memiliki lapisan silika pada kulit adalah rotan sega dan taman.
Peruntian rotan dapat dilakukan dengan menggunakan alat khusus disebut runti
jala atau dengan menarik rotan bolak-balik melalui lubang pada sepotong bambu
yang diikat berdiri pada sebatang pohon (Januminro, 2000)
5.
Pengeringan
Pengeringan rotan dilakukan di lapangan terbuka agar
rotan langsung terkena paparan sinar matahari. Lantai tempat pengeringan bisa
berupa tanah kering atau pelataran semen dengan drainase baik (Rachman dan
Hermawan, 2005). Rotan besar dikeringkan dengan cara disusun berdiri secara
silang menyilang hampir tegak lurus pada sandaran yang terbuat dari kayu atau
bambu (Rachman dan Hermawan, 2005). Untuk mendapatkan hasil pengeringan yang
merata dan warna yang cerah, rotan harus sewaktu-waktu dibalik (Rachman dan
Hermawan, 2005). Waktu pengeringan di musim kemarau hanya sekitar 1 minggu dan
di musim penghujan dapat mencapai 2-3 minggu untuk sampai pada kondisi kering
udara dengan kadar air sekitar 15-18% (Rachman dan Hermawan, 2005).
6.
Pengasapan
Untuk memperoleh rotan bulat kualitas WS (washed
and sulphurized) yang banyak diminta dalam dunia perdagangan, perlu
dilakukan pengasapan terhadap rotan yang telah dijemur/dikeringkan. Pengasapan
bertujuan untuk memutihkan warna kulit rotan, dengan proses pengelantangan (bleaching)
menggunakan asap belerang (gas SO2) (Rachman dan Hermawan, 2005). Selain itu,
pengasapan juga bertujuan untuk memasukkan asap belerang ke dalam pori-pori
rotan untuk meningkatkan ketahanannya terhadap serangan hama dan penyakit
apabila disimpan cukup lama dalam gudang (Januminro, 2000).
2.4.3 Letak Goegrafis Kelurahan Balearjosari
 Secara geografis
Kelurahan Balearjosari merupakan kelurahan yang berada di posisi paling Utara
sekaligus sebagai pintu gerbang masuk kota Malang dan berada di wilayah
Kecamatan Blimbing Kota Malang. Kelurahan balearjosari memiliki karakter
sebagai kawasan transisi yaitu kawasan yang berbatasan dengan Kabupaten Malang.
Luas lahan yang ada di Kelurahan Balearjosari adalah 151,1 Ha. Lahan terbangun
yang ada adalah seluas 78,7 Ha dan lahan tidak terbangunnya mencapai 72,4 Ha.
Kelurahan Balearjosari memiliki kepadatan penduduk yang tergolong rendah yaitu
292 penduduk/Ha. Prosentase perbandingan lahan terbangun dan tidak terbangun
adalah 52,02% : 47,98 %.
Secara geografis
Kelurahan Balearjosari merupakan kelurahan yang berada di posisi paling Utara
sekaligus sebagai pintu gerbang masuk kota Malang dan berada di wilayah
Kecamatan Blimbing Kota Malang. Kelurahan balearjosari memiliki karakter
sebagai kawasan transisi yaitu kawasan yang berbatasan dengan Kabupaten Malang.
Luas lahan yang ada di Kelurahan Balearjosari adalah 151,1 Ha. Lahan terbangun
yang ada adalah seluas 78,7 Ha dan lahan tidak terbangunnya mencapai 72,4 Ha.
Kelurahan Balearjosari memiliki kepadatan penduduk yang tergolong rendah yaitu
292 penduduk/Ha. Prosentase perbandingan lahan terbangun dan tidak terbangun
adalah 52,02% : 47,98 %.
Gambar
1. Peta kota Malang
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Jenis
penelitian ini adalah deskriptif-eksploratif dengan menggunakan metode survey
dengan teknik wawancara tidak terstruktur (Struktur Interview) dan
disertai dengan keterlibatan aktif peneliti dalam kegiatan proses pembuatan (Participatory
Etnobotani Appraisal).
3.2 Waktu dan Tempat
Penelitian
dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 06 Juni 2015 di Cindy Rotan Jl Raya
Balearjosari, Blimbing Malang.
3.3 Alat dan Bahan
Alat
yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kamera dan alat tulis. Adapun bahan yang digunakan
adalah rotan sebagai bahan dasar kerajinan.
3.4 Subjek Penelitian
Subjek
penelitian ini adalah orang yang mengetahui teknik-teknik pembuatan
produk-produk dari rotan.
3.5 Instrumen Penelitian
Data
hasil penelitian tentang Studi Etnobotani Kerajianan Anyaman Rotan Oleh
Masyarakat Kelurahan Belearjosari Malang Jawa Timur dengan menggunakan
instrument berupa wawancara disertai dengan observasi. Sedangkan bahasa yang
digunakan dalam wawancara adalah bahasa jawa halus berdasarkan bahasa
keseharian dan kesopanan kepada orang yang lebih tua.
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil wawancara dengan
karyawan pengrajin rotan di Balearjosari-Malang bapak Iwan (32 tahun) dapat
diketahui rotan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Pembuatan kerajinan rotan
tidak selalu menggunakan satu macam bahan, tetapi dapat dikombinasikan dengan
bahan lainnya. Dengan demikian hasil kerajinan lebih menarik dan bervariasi.
Rotan Cindy merupakan salah satu
home industri di kelurahan Balerjosari Malang yang memproduksi beebagai
kerajian berbahan dasar rotan. Home industri ini sudah diwariskan sejak
turun-temurun. Diperkirakan home industri ini berdiri sejak tahun 1975. Dalam
home industri ini terdapat sepuluh orang karyawan yang bertugas di
masing-masing bagian. Setiap karyawan mempunyai keahlian tersendiri dalam
menghasilkan kerajinan. Seperti bapak Iwan bertugas membuat kerangka kerajinan,
keudian bapak Mul menganyam hingga selesai. Alat-alat yang digunakan juga tidak
begitu rumit untuk dioperasikan hanya membutuhkan keahlian. Selama
pengoperasian tidak terdapat kendala karena bahan selalu tersedia pekerjaan
dapat diselesaikan di rumah.
4.2 Rotan Sebagai Bahan Dasar Kerajinan
4.2.1 Klasifikasi
Klasifikasi
tumbuhan rotan (Calamus sp) menurut Plantamor (2008) adalah sebagai
berikut.
Kingdom : Plantae
Divisi
: Magnoliophyta
Class : Liliopsida
Ordo : Arecales
Famili : Arecaceae
Genus : Calamus
Species : Calamus sp
4.2.2 Nama Lokal
Nama lokal rotan antara lain sumambu (Batak Karo),
simambo (Batak Toba), simambu (Minangkabau), semambu (Lampung), semabu
(Kalimantan Barat), Tantuwo (Dayak Kalimantan Tengah).
4.2.3 Bagian Rotan yang Digunakan
Bagian rotan yang paling umum digunakan yaitu bagian
batang rotan. Bagian batang rotan lebih banyak digunakan karena bagian ini
memiliki sifat, bentuk dan ukuran yang berbeda. Menurut Rachman dan Jasni
(2006) bentuk batang rotan umumnya silidris yang terdiri dari ruas-ruas dengan
ukuran 10-50 cm, sedangkan diameter berkisar 6-50 mm. Setiap ruas dibatasi oleh
buku yang terlihat pada bagian luar saja. Kulit batang rotan ada yang licin
misalnya pada bubuay (Plectocomia elongate Becc.) dan ada yang mengkerut
misalnya pada manau (Calamus manan Mig.)
Jenis rotan yang digunkan dalam kerajinan yaitu
rotan besar dan rotan kecil. Rotan besar dimanfaatkan sebagai kerangkan dasar,
sedangkan rotan kecil digunkan untuk bahan anyaman pada kerangka. Rotan besar
juga bisa dijadikan rotan dengan ukuran-ukuran tertentu sesuai dengan
kebutuhan.
4.2.4 Jenis Bahan Kerajinan Anyaman
Pembuatan kerajinan anyaman berasal
dari batang rotan yang sudah cukup umur. Untuk memperoleh hasil yag bervariasi
dapat dilakukan dengan penambahan dengan bahan lain. Bahan yang paling sering
ditambahnkan yaitu:
1. Serat
Mendong
Mendong adalah sejenis rerumputan yang hidup di
daerah berair seperti sawah atau rawa. Kebanyakan mendong diproses menjadi
tikar dengan cara dianyam, pada saat penganyaman mendong harus dibasahkan
dahulu agar tidak mudah putus. Mendong dapat juga dijalin dibuat rara maupun
dianyam. Selain menjadi tikar, mendong dapat menjadi beberapa jenis kerajinan
anyaman seperti tas, topi, dan ada pula yang dikombinasikan dengan rotan untuk
diproduksi kursi dan perabotan rumah tangga.
2. Serat
Eceng gondok
Tanaman enceng gondok adalah tanaman gulma atau
sejenis tanaman liar di air, hidup dirawa-rawa. Seperti halnya mendong enceng
gondok yang akan digunakan harus dicuci dan dikeringkan, diberi warna jika
perlu dan diberi pengawet agar menjadi tahan lama. Kemudian eceng gondok
dianyam seperti kepangan rambut. Anyaman enceng gondong dapat dibuat kerajinan,
seperti tas, sandal, alas duduk, tempat tisu, bahkan kursi.
3. Serat
Pelepah Pisang
Serat pelepah pisang
dapat dijadikan bahan tambahan dalam kerajinan anyaman. Pelepah pisang yang
akan digunakan harus dikeringkan terlebih dahulu hingga kandungan air menjadi
kering. Setelah itu pelepah pisang di pisahkan menjadi bagian-bagian kecil dan
dipelintir.
4.2.5 Perolehan Rotan
Rotan yang akan dibuat kerajinan
berasal dari Kalimantan yang dijual oleh pengepul di Surabaya. Sedangakan serat
eceng gondok, mendong dan pelepah pisang diperoleh dari Kecamatan Wajak
Malang.
4.3 Teknik Penganyaman Rotan
Beberapa
langkah dalam pembuatan kerajinan anyaman rotan adalah sebagai berikut
1.
Tahap persiapan,
pada tahap ini rotan dipotong-potong sesuai dengan ukuran sebagai kerangka
dasar.
 |
2.
Pewarnaan, pada
proses ini bahan yang akan didesain diwarnai sesuai dengan keinginan. Pewarna
yang diguakan dapat berupa pewarna sintetis atau pewarna makanan. Setelah
diwarnai, kemudian dikeringkan.
3.
Pembuatan
kerangka, pada proses pembuatan kerangka digugunakan alat pembengkok agar rotan
tersebut bisa dilekukan sesuai dengan model desainnya. Kemudian dibuat kerangka
dasar sesuai dengan desain barang yang akan dibuat
 |
4.
Penganyaman,
proses penganyaman bertujuan untuk menutupi kerangka yang sesuai dengan jenis
desainnya. Jenis anyaman yang sering digunakan dalam anyaman rotan yaitu teknik
anyaman tunggal. Pada teknik ini rotan dianyam satu-satu (secara
tunggal). Caranya, rotan dianyam selangkah demi selagkah, satu demi satu
dengan memasukkannya secara menyilang. Setelah rotan dianyam, pada ujung
anyaman di staples agar anyaman tidah lepas dari kerangkanya.
 |
4.4 Kelebihan Dan Kelemahan Rotan
Rotan
menjadi material yang mendominasi dunia furniture. Rotan memiliki kelebihan
mudah dibentuk, mudah dijadikan berbagai jenis furniture bahkan dapat digunakan
sebagai bahan dinding, plafon maupun elemen interior berskala besar. Rotan juga
dapat digunakan dengan mudah untuk berbagai barang yang berukuran kecil karena
strukturnya yang liat, berurai dan tidak mudah patah. Rotan juga mempunyai
warna yang khas dan unik.
Agar
dapat menggunakan rotan dengan baik maka perlu diperhatikan kelemahan rotan,
diantaranya mudah terbakar, kandungan sari tepung yang sangat tinggi
mengakibatkan strukturnya rentan diserang rayap, serta daya tahannya yang
kurang baik terhadap air. Namun demikian dengan perlakuan yang baik dan bersih
niscaya rotan menjadi bagian yang menarik untuk menghiasi ruang-ruang di rumah.
BAB V
PENUTUP
5.1 Simpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab IV
dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut.
1. Jenis
tumbuhan yang dapat dimanfaatkan dalam kerajianan anyaman oleh masyarakat
kelurahan Balearjosari berasal dari rotan, bambu,
2. Sumber perolehan tumbuhan untuk bahan pembuatan kerajinan
anyaman yaitu rotan berasal dari kalimantan dan dipasarkan di surabaya. Eceng
gondok, mendong, dan serat pelepah pisang berasal dari kecamatan Wajak Malang
3. Organ yang dimanfaatkan dalam kerajinan anyaman yaitu batang
rotan, pelepah pisang, batang eceng gondok, batang mendong
4. Teknik
pembuatan kerajinan anyaman
5.
Kelebihan rotan sebagai bahan kerajinan anyaman mudah
didapat, rotan mempunyai sifat-sifat yang alami yaitu
elastis, mudah dibentuk, ringan, tahan terhadap perubahan cuaca, dan mempunyai
warna alamiah yang menarik. Kelemahan rotan mudah terbakar, kandungan sari
tepung yang sangat tinggi mengakibatkan strukturnya rentan diserang rayap.
5.2 Saran
Berdasarkan
simpulan di atas, ada sejumlah saran yang perlu disampaikan, yaitu pengetahuan
pemanfaatan kerajianan anyaman rotan perlu ditingkatkan agar nilai seni ini
tidak hilang dan dapat dikenal baik secara nasional maupun internasional.
DAFTAR RUJUKAN
Dransfield, J. dan N. Manokaran. 1996. Sumber Daya Nabati Asia Tenggara 6 Rotan.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Januminro, CFM. 2000. Rotan Indonesia Potensi Budidaya Pemungutan
Pengelolaan Standar Mutu dan Prospek Pengusahaan. Yogyakarta: Kanisius
Jasni, D. M dan N. Supriana. 2000. Sari
Hasil Penelitian Rotan. Himpunan Sari Hasil Penelitian Rotan dan Bambu. Bogor:
Pusat Penelitian Hasil Hutan.
Jasni,
Krisdianto, Titi Kalima dan Abdurachman. 2012. Atlas Rotan Indonesia Jilid 3. Pusat Penelitian dan Pengembangan
Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan.
MacKinnon, K.,G. Hatta, H.Halim, dan
A.Managalik. 2000. Seri Ekologi Indonesia
Buku III Ekologi Kalimantan.
Jakarta: Prenhallindo
Martin GI. 1998. Etnobotani. M.Mohamed, penerjemah.
Gland Switzerland: Kerjasama Natural History Publication (borneo), Kota
Kinibalu dan World Life Fund for Nature.
Rachman
Osly dan Jasni. 2006. Rotan Sumberdaya,
Sifat dan Pengolahannnya. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan.
Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Bogor: Departemen Kehutnanan.
Rachman,
O. 1996. Peranan Sifat Anatomi, Kimia dan Fisis terhadap Mutu Rekayasa Rotan. Disertasi Doktor. Bogor: Institut
Pertanian Bogor.
Soekarman
dan Riswan, S. 1992. Status Pengetahuan Etnobotani di Indonesia.
Prosiding Seminar Etnobotani.
LAMPIRAN



 |
|||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||
 |
 |
||||||||||||
 |
|||||||||||||
 |
|||||||||||||
 |
|||||||||||||


![[review] NO MERCY 2010; Penemuan Mayat Mutilasi](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEmnXTMpE7jSLNCzXhdc-vhIzW2aNKVJe2GzEImAaq99Gzf1HsM1LuNH4JmWWfrsW7uHVcaqfRIz98Z4sFpptBEPMcJ_Mg3rJCJ-0kASgC0SneW1zw5T4yM1WtrXmNbyMp0DxH8eJKp4da/w680/1601656440883213-0.png)
![[Review] THE SILENCED 2015; Hilangnya Para Gadis Asrama](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4ijuo7N1GOor2W2bZ1xSsJUtX42ZDdp-5Sef9-tJMZUlqFsAuRxNZsHtrCvqKwbdVL1MQT2DvqnyRfP8t_s8iGk8GR4ckVmvR1RF4g59Ky5fWG2t2QmmueOdxBI1zHX3BqUULbFQNlDn5/w680/1601571453792951-0.png)
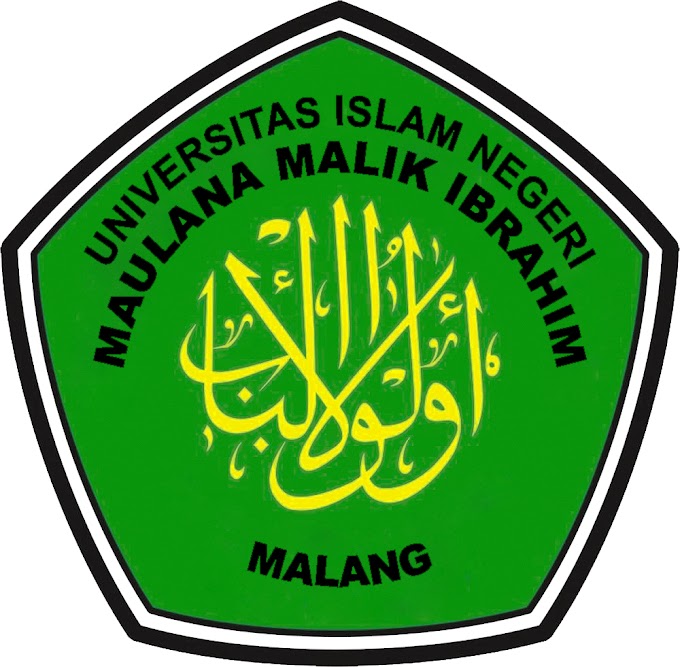


![[Review Buku] TUHAN MAHA ROMANTIS; Ketika Ekspresi Rindu adalah Doa, Tak Cinta yang Tak Mulia](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkdcSwo1goT6w8SY20MHRG-rYkfvtGFE4D52JunBanS-SUZJHNrKdtmNX3hy9fARHMzRrjlDTxrsfUAVo5tVf0gZi1J1KPArO_wPqCUYW_GjuaTHrOrKPkONscdCy8LoogVgwGPNRXq9G-/w680/WhatsApp+Image+2020-08-18+at+14.09.31.jpeg)
![[Review] APOCALYPTO 2006; Berakhirnya Peradaban Suku Maya](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidioNdAOEqi_K9OHLrl58eP1GXxl21J2pnpUVJRsnw7JuZ0wuFXrf-mv-K6kzj3JarDA_d4sjpAybpYG62wP_RlKZUIxDx5EKnII4fm4-UQIbPGFmPfmmPwIULm1PA7BsPgw2yKrpbIGH0/w680/1600789966383704-0.png)

0 Komentar